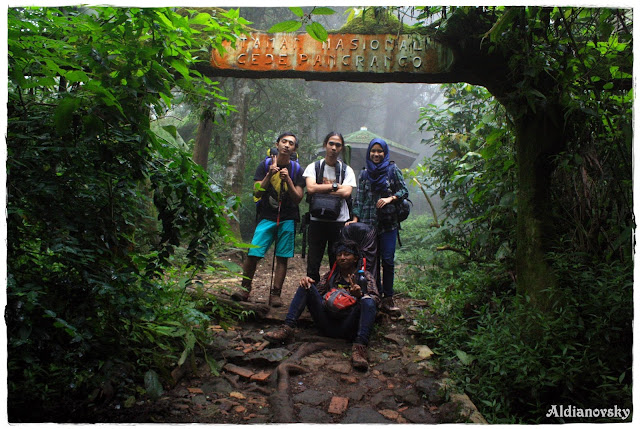Awan mendung berarak diatas kepala kami pagi
itu, padahal waktu baru saja menunjukkan pukul 09.40 WIB. Jumat tanggal 15
April 2016, saya dan keempat rekan saya, Syaiful (Ipul), Riki, Linda dan Randi,
mulai bergegas meninggalkan pos pemeriksaan di jalur Putri. Tidak ada kesan
yang menyenangkan ketika tengah melalui prosedur pemeriksaan di pos ini
lantaran salah seorang petugas yang memeriksa kami terlalu berlebihan dalam
memberikan saran dan masukan sehingga terkesan menggurui. Berusaha untuk tidak
turut memperkeruh suasana di pagi hari, maka saya cukup diam tanpa berkomentar
apapun juga.
 |
Syaiful, Randi, saya dan Linda saat baru saja
tiba di depan gang menuju pos pemeriksaan gunung Putri.
|
 |
Sarapan terlebih dahulu di pasar Cipanas
sebelum memulai pendakian.
|
 |
Desain sticker untuk pendakian kali ini.
|
Tampilan fisik gunung Gede yang
seharusnya tampak jelas, pagi itu justru bersembunyi ditelan pekatnya
halimunan. Udara sejuk di ketinggian sekitar 1.400 meter itu mulai menyambut
kedatangan kami berlima, hangatnya mentari pagi seolah tertahan oleh sekawanan
kabut tebal yang turun menyusuri lereng gunung. Saya bersama keempat kawan saya
berjalan diantara ladang dan perkebunan warga yang sekaligus menjadi titik awal
perjalanan kami menuju surganya gunung Gede, alun-alun Suryakancana. Tanaman
brokoli, wortel, bawang daun dan sawi tampak mendominasi ladang yang kami
lalui. Setelah melewati jembatan dan sebuah sungai kecil, akhirnya jalanan
mulai menanjak dan perlahan menjauh dari ladang serta perkebunan warga.
 |
Istirahat
sekaligus melakukan pengecekan simaksi dan perlengkapan di pos
pemeriksaan gunung Putri.
|
 |
lokasi gunung Gede dilihat dari Google map.
|
 |
Peta rute pendakian gunung Gede via Putri –
Cibodas.
|
Suasana seketika menjadi gelap saat
kami memasuki hutan pegunungan dimana cahaya matahari tidak leluasa menembus
rimbunnya kanopi pepohonan yang tingginya bisa mencapai 20 meter dari permukaan
tanah. Dikarenakan tidak terjamah oleh sinar matahari juga tingkat
kelembabannya yang terbilang tinggi, tak ayal dahan-dahan pohon dan bebatuan
yang ada didalam hutan itu nyaris tertutup oleh tumbuhan lumut. Derap langkah
dan dengusan nafas terdengar saling memburu diatas tanjakan berbatu, detak
jantung semakin cepat dan kepala sedikit pening, padahal perjalanan belum ada
setengahnya. Tidak lama kemudian kabut tebal kembali menggerayangi setiap sudut
belantara, menimbulkan kesan hening mencekam. Kami terus berjalan meski
perlahan hingga akhirnya kami menjumpai sebuah shelter dan gapura beton bertuliskan “Taman Nasional Gede
Pangrango”, siang itu saya dan kawan-kawan berhasil menjejakkan kaki di pos I,
Legok Leunca.
 |
Linda ketika berada di antara perkebunan
warga.
|
 |
Berselfie di persimpangan jalur sambil
menunggu kedatangan Ipul dan Riki.
|
 |
Track yang
gelap dan berkabut mulai menyambut manakala kami memasuki hutan.
|
1.
POS I: Legok Leunca (1.900 mdpl)
Kami tiba di pos I pada pukul 11.02
WIB, suasananya sedikit terang dengan dilengkapi sebuah shelter yang atap dan penopangnya dibentuk menyerupai payung. Tanah
di tempat itu terbilang datar dan cukup untuk menampung sekitar tiga sampai
empat buah tenda, namun demikian sangat jarang pendaki yang hendak berkemah
disitu.
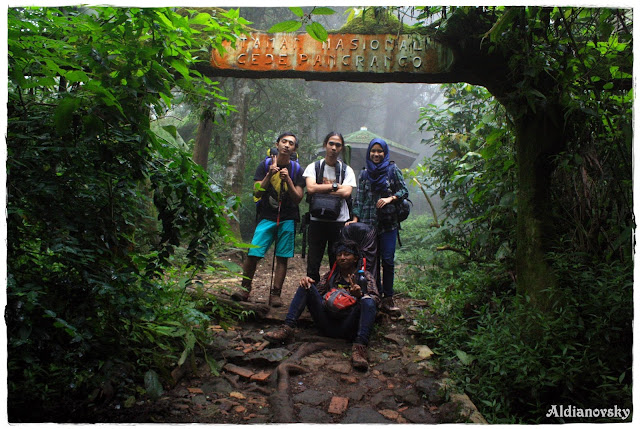 |
Tim ketika baru menginjakkan kaki di pos I,
Legok Leunca.
|
 |
Sebelum
tiba di shelter Legok Leunca, para pendaki akan disambut oleh Gapura yang telah ditumbuhi lumut
terlebih dahulu.
|
Riki dan Ipul terlihat asyik dengan
kepulan rokoknya, sementara saya lebih memilih untuk membaringkan diri diatas
tempat duduk yang terbuat dari semen dan bebatuan kali. Rasa kantuk hinggap
manakala kabut tebal lagi-lagi menghampiri kami, apalagi saat itu kondisi saya
memang belum tidur dari semenjak H-1. Tak lama kemudian, terdengar suara
beberapa orang dari arah luar gapura hingga akhirnya tampak dari balik rerimbunan
sosok empat orang pendaki lengkap dengan peralatan hikingnya. Mereka semuanya lelaki, tapi usia mereka sudah jauh dari
kata muda. Perjalanan hidup telah menganugerahi mereka dengan helai-helai uban
di rambutnya, kulit dan wajah mereka tampak jelas mengeriput, meski demikian
postur tubuh dan nafas mereka terbilang masih bisa diadu dengan pendaki yang masih
belia.
 |
| Plang
informasi milik TNGGP tentang kekayaan flora dan fauna yang ada didalam kawasan
gunung Gede Pangrango. |
Kami berdiri dan menyalami mereka
satu-persatu, dari penampilannya saya sudah menduga kalau keempat orang
tersebut adalah para pendaki senior. Ternyata mereka berasal dari Jakarta dan
sama-sama teman semasa kuliah di ISTN Cikini, Jakarta Pusat. Rata-rata usia
mereka sudah lebih dari setengah abad, hampir seusia orang tua saya. Kami
mengobrol penuh keakraban, bahkan tidak ada kesan menggurui walaupun jam
terbang serta pengalaman mereka sudah berada jauh diatas saya ataupun keempat
rekan saya. Rasanya ingin tersenyum geli oleh kelakuan segelintir pendaki jaman
sekarang yang merasa dirinya sudah lebih tahu, lebih berpengalaman dengan
“menaklukkan” puncak-puncak gunung, merasa dirinya paling benar dalam bertindak
atau berargumen, serta cenderung tidak menghargai pendaki lain, padahal
keangkuhannya itu merupakan sebuah blunder
bagi reputasinya sendiri. Meski demikian, saya yakin masih banyak pendaki di
era sekarang yang berwawasan dan berpengalaman luas namun mereka tetap tampil low profile.
 |
| Tengah
bercengkrama dengan empat orang pendaki senior di shelter pos I. |
Pukul 11.40, kami berpamit diri pada
keempat pendaki tua tadi untuk kembali melanjutkan perjalan menuju pos II yang
berjarak sekitar 400 meter dari shelter
Legok Leunca.
2.
POS II: Buntut Lutung (2.300 mdpl)
Jalanan menanjak menuju pos kedua ini
sudah mulai sedikit menguras stamina. Disini, tanah yang licin akibat ditumbuhi
lumut dan akar-akar pohon yang mencuat dari permukaan tanah akan lebih sering
kita jumpai ketimbang track berbatu
seperti jalur sebelumnya. Dengan nafas yang terengah-engah, saya menggapai
tembok sebuah bangunan yang rusak dan sepertinya sudah lama terbengkalai, saya
duduk bersandar pada tembok tersebut sambil mengatur nafas. Desau angin sejuk
menyelisik dari balik ranting serta dedaunan. Pekik Owa Jawa (Hylobates Moloch) terdengar bersahutan,
seolah jadi musik pengiring yang menemani perjalanan kami.
 |
Mengatur nafas dulu sesampainya di pos II.
|
 |
| Wajah-wajah
yang tengah didera rasa lelah. |
Di tempat ini sama sekali tidak ada
ruang bagi para pendaki untuk membuka tenda karena minimnya tanah yang datar.
Selang beberapa menit, Ipul, Riki dan Randi tiba. Kami hanya beristirahat
sebentar saja disini karena kami menargetkan tiba di alun-alun Suryakancana
sebelum pukul empat sore.
3.
POS III: Lawang Seketeng (2.500 mdpl)
Beberapa meter sebelum saya tiba di pos III, mulai terdengar
hiruk-pikuk dan gelak tawa dari para pendaki yang tengah beristirahat.
Setibanya saya di tempat itu, tampak shelter
di pos tersebut sudah terlebih dulu dibooking
pendaki lain sehingga kami harus puas dengan beristirahat atau sekedar duduk di
lembabnya sebuah batang pohon yang telah tumbang.
 |
| Shelter di pos III yang dipenuhi oleh beberapa orang
pendaki. |
Di pos III ini, suhunya sedikit lebih
hangat dikarenakan posisinya yang hampir berada di ketinggian 2.500 meter
dimana pepohonan yang menjulang ke angkasa tidak sebanyak dan serapat saat kami
berada di pos-pos sebelumnya sehingga ada celah lebar yang mampu diterobos oleh
sinar matahari. Saya kembali merasakan kantuk yang sangat luar biasa sehingga
saya memutuskan untuk tidur disisi jalur pendakian, sementara itu Riki dan
Randi lebih memillih memasak air untuk membuat teh hangat. Seorang pendaki yang
juga merangkap sebagai pedagang souvenir
asal Karawang, datang menghampiri. Ia menjajakan barang dagangannya kepada kami
namun sepertinya hanya Riki yang tertarik untuk membelinya. Saya terbangun oleh
kehadiran orang tersebut. Iseng-iseng, saya pun menanyakan waktu yang harus
kami tempuh dari pos ini sampai ke alun-alun Suryakancana pada orang itu, dan dia
bilang sekitar satu jam lagi. Saya sempat ucapannya, sebab dari beberapa
pendaki yang turun dan berpapasan dengan kami hampir semuanya memberikan jawaban
yang sama. Apalagi saya hafal betul kelakuan pendaki yang rata-rata suka
memberikan harapan palsu pada pendaki lainnya agar mereka tetap semangat menuju
tempat yang dituju. Setelah memasukkan peralatan masak dan gelas plastik
kedalam carrier, kami pun kembali melanjutkan
perjalanan, semuanya berharap tiba di lembah Suryakancana sebelum senja.
 |
Tidur disisi jalan pun menjadi pilihan
terbaik saat rasa kantuk tak lagi bisa diajak berkompromi.
|
4.
POS IV: Simpang Maleber (2.625 mdpl)
Dari mulai shelter
Lawang Seketeng, jalur menanjak yang cukup melelahkan sudah siap menyongsong
kami. Nafas mulai tidak beraturan, timbul tenggelam dipermainkan terjalnya
tanjakan. Dari kelima orang di tim ini, hanya Randi yang stamina dan nafasnya masih
terbilang stabil.
 |
Ipul dan Riki ketika beristirahat antara pos
III dan pos IV.
|
Dengan ditemani seorang pedagang minuman dan mie instant, Randi sudah
lebih dulu melesat mendahului saya, Ipul, Linda dan Riki. Ia optimis betul
kalau alun-alun Suryakancana sudah berada sangat dekat didepan mata, tidak
seperti kami berempat yang merasa perjalanan ini bagaikan tanpa penghujung.
Beban pada carrier ditambah
tanjakan-tanjakan “gemes” yang seperti tidak ada habisnya membuat stamina saya,
Linda, Ipul dan Riki betul-betul habis terkuras, bahkan untuk mendaki satu anak
tangga pun rasanya dibutuhkan nafas yang panjang dan energi yang banyak. Entah
kapan tanjakan-tanjakan seperti ini akan berakhir, pikir saya saat itu.
 |
| Tetap
beriringan dalam meniti setiap tanjakan. |
Sesampainya di pos IV yang
penampakannya hanya berupa tanah datar namun tidak cukup lega untuk beristirahat
karena ada beberapa batang pohon yang roboh, saya pun segera meluruskan kedua
kaki yang mulai terasa ngilu. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.35 WIB, tidak
lama lagi matahari akan lenyap dari perederannya di langit sedangkan kami
bertiga masih berada di jalur pendakian, di tengah hutan. Target saya untuk
bisa sampai di alun-alun Suryakancana sebelum jam empat sore, kandas sudah.
 |
Beban pada carrier kerapkali membuat langkah Linda tertahan.
|
Dengan waktu yang tersisa tidak lebih
dari satu setengah jam saja untuk menghabiskan cahaya senja, kami berempat pun
akhirnya kembali melangkahkan kaki mengikuti tanjakan-tanjakan yang sepertinya
masih betah bercanda dengan saya dan ketiga rekan saya.
5.
Alun-alun Suryakancana (2.750 mdpl)
Riki dan Ipul sudah hilang entah
kemana, sementara saya dan Linda masih berkutat dengan tanjakan ala jalur Putri.
Sudah pukul lima sore namun lembah Suryakancana yang ada di benak saya belum
juga terlihat. Sedikit gelisah, ada perasaan khawatir kemalaman di jalur
pendakian sebelum sampai di tempat tujuan. Sesekali kami berdua menghentikan langkah
untuk beristirahat lalu melanjutkan perjalanan lagi, begitu dan seterusnya
sampai suatu ketika ada seseorang yang meneriaki saya dari arah depan, ternyata
orang itu adalah Randi yang memang berinisiatif untuk menjemput kami berdua. Ia
menyemangati saya dan Linda untuk terus memacu langkah.
 |
Menyatukan semangat diantara nafas yang sudah
mulai turun naik menyusuri jalan menanjak.
|
“Ayo kak! Didepan udah sampe (alun-alun Suryakancana)”
ujar Randi seraya mengambil alih carrier
yang saya bawa. Saya dan Linda mempercepat langkah agar segera bisa
menginjakkan kaki di alun-alun Suryakancana dan memang tidak beberapa jauh dari
tempat Randi menyusul tadi, jalanan sudah tidak lagi terjal dan menanjak,
dengan kata lain cenderung datar. Sangat kontras perbedaannya ketika kami masih
berada didalam koridor hutan yang dikelilingi oleh dahan dan akar pepohonan bila
dibandingkan dengan kondisi di jalur ini yang tak lama lagi akan mengarahkan
kami pada alun-alun Suryakancana. Suasana jadi terang benderang tanpa dahan dan
batang yang jadi penghalang, saya dan Linda akhirnya sampai juga di tempat
tujuan. Inilah alun-alun Suryakancana, setitik surga di gunung Gede.
 |
Ekspresi kegembiraan ketika saya dan Linda
akhirnya tiba di alun-alun Suryakancana beberapa saat sebelum matahari
tenggelam.
|
“Subhanallah”, hanya satu kata itu
saja yang berulangkali terucap dari mulut ini. Tidak ada kata-kata yang bisa
mengungkapkan atau melukiskan kekaguman serta rasa takjub saya dan Linda
manakala kami berdua tiba di alun-alun Suryakancana yang tersohor itu. Saya,
Linda dan Randi melipir ke sisi kiri untuk menuju ujung dari lembah tersebut. Semburat
awan jingga di penghujung senja seolah mempercantik tampilan alun-alun
Suryakancana timur yang mashyur. Perdu jenis Anaphalis Javanica atau yang lebih popular di telinga para pendaki
dengan julukan si bunga abadi, tampak tumbuh subur di padang rumput ini.
Sayangnya kami datang di waktu yang tidak tepat, tidak ada satupun bunga
Edelweiss yang terlihat sedang mekar. Pohon-pohon Cantigi gunung yang anggun
turut berbagi keindahan dengan warna daunnya yang hijau dan merah cerah, namun kerapkali
para pendaki tak mengetahui namanya padahal mungkin sudah berkali-kali mereka
melihat rupanya. Tak ingin kehilangan moment
menjelang senja, saya dan Linda segera saja mengabadikan gambar dengan
kamera masing-masing.
 |
Masih dengan wajah yang kelelahan.
|
 |
Ketika rasa letih dan takjub berbaur dalam
ketertegunan.
|
 |
Ipul dan ekspresi datarnya.
|
 |
| Riki
dan peralatan huntingnya. |
 |
| Hanya
Randi yang stamina juga nafasnya masih stabil. |
Setelah puas berfoto ria di
penghujung lembah Suryakancana timur, kami berlima segera meninggalkan tempat
itu untuk menuju ke alun-alun Suryakancana barat. Gumpalan awan menelan
sisa-sisa cahaya senja, sekarang langit beranjak gelap gulita. Derap langkah
kaki kami membuyarkan keheningan di lembah yang diapit oleh puncak Gede dan
puncak Gumuruh itu. Sudah nyaris tiga puluh menit kami berjalan kaki menyusuri
jalur yang ada di alun-alun Suryakancana ini, namun kami belum juga menemui
satupun tenda dari pendaki yang sedang berkemah. Tidak lama kemudian saya
mendengar gemericik air, entah sungai entah aliran air biasa. Suaranya seperti
berada disebelah kiri saya, disekitar kaki gunung Gumuruh. Bersamaan dengan itu
pula kami mendengar suara gelak tawa dan suara orang-orang yang tengah
bercengkrama. Kami melipir kearah kanan ketika kami melihat beberapa tenda
milik pendaki lain yang sudah terpasang sekaligus tempat dimana sumber dari
suara-suara tadi berasal. Setelah memilah lahan yang cukup datar serta
terlindungi tanaman Cantigi dan Edelweiss, saya, Ipul dan Randi segera
mendirikan dua buah tenda yang kami bawa.
 |
| Berjalan
menyusuri hamparan alun-alun Suryakancana timur. |
 |
| Pemandangan kala senja di alun-alun Suryakancana timur dengan latarbelakang kota Cianjur. |
6.
Suryakancana, nama besar yang melegenda
Dengkuran Riki seolah menyaingi desau angin yang tengah
berpatroli dari satu sisi lembah ke sisi lembah yang lain. Malam itu, cuma saya
dan Ipul saja yang belum bersedia memejamkan mata hanya demi bisa menikmati indahnya
lukisan Sang Pencipta alam raya. Cahaya rembulan yang belum bulat sempurna
tetap bisa menjamah hamparan padang rumput di Suryakancana. Sementara itu,
bintang-bintang perlahan menampakkan wujudnya dan memamerkan kilaunya di
angkasa. Saya dan Ipul menyaksikan atraksi alam raya tadi diluar tenda sambil
tak hentinya menyeruput teh tubruk hangat. Malam terasa syahdu dibawah rengkuhan
sinar rembulan, semakin malam semakin senyap suasana. namun dinginnya udara
saat itu betul-betul menyadarkan kami untuk tidak terlalu lama berada diluar
tenda, terlebih saya yang sama sekali tidak mengenakan jaket atau mantel.
DIALOG SUNYI DI LEMBAH SURYAKANCANA
Nyaman
yang bukan karena dekapan
Malam dan gemintang bersedekah keindahan
Bisik halus sang angin terabaikan
Udara dingin isyarat sebuah ucapan
Santunnya salam persahabatan...
Saat tubuh terpaku di teduhnya pancar
rembulan
Wahai, alun-alun Suryakancana...
Setitik surgawi sarat pesona
Tulus ikhlas haturkan Edelweiss-Edelweiss muda
Yang kadang bernasib naas di tangan-tangan
durjana
Disini, di alun-alun Suryakancana
Dimana embun lembah lepaskan dahaga
Dibawah langit bersulam cahaya
kurambah nikmat dihamparan mahakarya-Nya
Bogor, 27 April 2016
 |
Malam itu, Ipul menjadi juru masak istana
sedangkan Riki yang jadi kaisarnya.
|
Alun-alun Suryakancana memang terbilang
luas dan besar, layaknya nama eyang Suryakancana yang melegenda di tatar Sunda.
Pemberian nama lembah Suryakancana pun bukan tanpa alasan mengingat putra dari
Raden Jayasasana atau yang lebih dikenal sebagai Raden Aria Wira Tanu Datar I alias
eyang Cikundul ini memang bersemayam di gunung Gede. Masyarakat Cianjur meyakini
tokoh ini memiliki istana tak kasat mata yang terletak tepat di hamparan padang
rumput seluas 50 hektare tersebut, sehingga mereka menyebutnya dengan nama
alun-alun Suryakancana.
Secara terminologi, kata Suryakancana
memiliki arti yitu, cahaya matahari yang berwarna keemasan. Arti nama tersebut
menyerupai kejadian yang pernah dialami oleh ayahanda dari eyang Suryakancana,
eyang Wira Tanu Datar I. Ketika itu putri dari raja jin muslim di timur tengah,
sedang melakukan perjalanan di angkasa. Tiba-tiba ia melihat ada seberkas
cahaya sinar berwarna keemasan dan menyilaukan yang sanggup menerobos atmosfer
bumi hingga mencapai angkasa raya. Merasa penasaran akan sumber cahaya itu,
sang putri jin pun terbang menuju bumi dan menyusuri cahaya tadi sampai
akhirnya ia menemui seorang manusia paruh baya yang tengah berkhalwat, rupanya
cahaya keemasan yang mampu menyeruak hingga menembus lapisan terluar dari bumi
tadi bersumber dari diri lelaki tua tersebut. Sang putri jin merasa takjub dan
terpesona dengan keindahan yang terpancar dari si petapa yang merupakan eyang
Jayasasana atau eyang Wira Tanu Datar I. Ia pun akhirnya segera kembali menemui
ayahandanya dan melaporkan hal itu, sang putri juga menceritakan perasaan
kagumnya kepada si petapa hingga akhirnya timbul keinginan untuk menjadikan
lelaki tua itu sebagai suaminya. Sang raja jin merestui anak putrinya menikah
dengan petapa tersebut, setelah kedua jin muslim itu menemui Wira Tanu Datar I
untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Eyang Wira Tanu Datar I tidak langsung
menyetujui, namun sebelumnnya Beliau memohon diri terlebih dahulu untuk bertafakur
dan memohon petunjuk dari Yang Maha Esa. Setelah mendapatkan petunjuk, Beliau
akhirnya mau menikah dengan putri raja jin tersebut. Dari pernikahannya itu,
Beliau dikaruniai seorang putra bernama Suryakancana dan seorang putri bernama
Endang Sukaesih.
Eyang Suryakancana dan Endang
Sukaesih memiliki darah setengah manusia dan setengah jin, namun Endang
Sukaesih menikah dengan menusia sehingga memiliki keturunan hingga saat ini.
Sementara itu, eyang Suryakancana memilih tidak menikah dan memutuskan untuk bertapa
di gunung Gede hingga tiba masanya bagi Beliau menyaksikan pertunjukkan di
akhir jaman nanti. Adik kandungnya, Endang Sukaesih, memilih untuk bersemayam
di gunung Ceremai.
Sempat geli juga saat saya membaca
sebuah artikel yang menyebutkan kalau Prabu Silihwangi merupakan anak kandung dari
eyang Suryakancana. Sungguh tulisan yang sangat menggelitik perut orang Sunda,
bagaimana mungkin eyang Suryakancana yang tidak menikah bisa memiliki anak?
Selain itu, era saat eyang Suryakancana lahir ke bumi adalah sekitar
pertengahan abad ke 17 sedangkan kerajaan Pajajaran sendiri berakhir pada abad
ke 16. Itu artinya, eyang Suryakancana tidak pernah mengalami masa dimana Sri
Baduga Maharaja berkuasa sekalipun Beliau masih memiliki trah Pajajaran yang
sangat kuat. Entah pihak mana yang menulis artikel tersebut, apakah itu segelintir
orang yang sentimen terhadap Sunda ataukah memang orang iseng yang hanya sekedar
ingin berbagi cerita.
7.
Selamat Pagi...!
Suara orang-orang yang sedang
bercanda dan tertawa diluar tenda telah membangunkanku dari tidur. Sinar
matahari pagi yang mengenai langsung pada tenda membuat tubuh ini jadi hangat.
Saya mulai keluar perlahan dari kantung tidur dan membuka resleting tenda,
ternyata diluar sudah ada Ipul, Riki dan Randi yang sedang membuat sarapan.
Riki, Randi dan Linda baru saja turun dari puncak Gede untuk memburu sunrise, hanya saja mereka belum
beruntung karena objek yang diburu ternyata sudah terlebih dahulu mencuat ke
angkasa sebelum mereka berhasil menjejakkan kakinya di titik tertinggi.
 |
Penampakan gunung Salak yang terlihat dari
puncak gunung Gede.
|
 |
Pagi hari yang berkabut ketika Linda baru
saja menjejakkan kakinya di puncak Gede.
|
Saya beranjak menuju tengah alun-alun
untuk menghangatkan badan yang kedinginan dari sejak tadi malam. Pagi itu
tampak beberapa pendaki remaja yang asyik berfoto ria dengan menggunakan
tongkat narsisnya. Disebelah timur alun-alun, terdapat sekelompok pendaki yang
sepertinya baru saja tiba dan mereka terlihat sedang beristirahat di cekungan
yang berada tidak jauh dari sumber air. Saya menatap ke arah utara dimana
terpampang dinding alam yang agak lonjong memanjang berbalut rimbunnya
pepohonan Cantigi, yang sekaligus menjadi titik tertinggi di tempat ini. Ya,
itu adalah puncak dari gunung Gede yang tingginya hanya terpaut beberapa puluh
meter lebih tinggi dari sesosok bukit yang berada dihadapan saya, puncak
Gumuruh. Siapa yang sangka kalau sepanjang alun-alun Suryakancana ini dulunya
merupakan lubang kawah hasil erupsi besar-besaran dan akhirnya ditumbuhi
belukar serta tanaman perdun seperti Edelweiss dan Cantigi gunung. Pada saat
gunung Gede belum mengalami serangkaian letusan yang pada akhirnya membuat
cekungan lembah antara puncak Gede dan puncak Gumuruh seperti sekarang ini, besar
kemungkinan gunung Gede memiliki ukuran yang lebih tinggi dari pesaing abadinya,
Pangrango. Apabila dilihat dari salah satu kutipan yang terdapat pada naskah
Bujangga Manik, disitu tertera kalimat;
“Setelah tiba di Putih Birit, aku harus
melakukan sebuah pendakian yang panjang (yang aku lakukan sedikit demi sedikit).
Setelah tiba di Puncak, aku duduk di atas sebuah batu pipih, dan mengipasi
diriku sendiri. Di sana ia melihat pegunungan: Terdapat Bukit Ageung
(sekarang Gunung Gede) , tempat
tertinggi dalam kekuasaan Pakuan”.
Naskah Bujangga Manik diperkirakan ditulis
pada akhir abad ke 13 sehingga bisa dipahami apabila Pangeran Jaya Pakuan a.k.a
Bujangga Manik menyebut gunung Gede sebagai titik tertinggi di tatar Pasundan
pada saat itu sebab gunung Gede baru mulai erupsi pada tahun 1747/1748, 1761,
1780, 1832, 1840, 1852, 1886, 1940, 1950, dan letusan yang terakhir kalinya
pada tahun 1957. Dengan jumlah letusan sebanyak tadi, wajar bila gunung Gede
memiliki empat buah kawah, yakni; kawah Lanang, kawah Wadon, kawah Ratu dan
kawah Baru. Pada letusan yang pertama, aliran lavanya mengalir sejauh 2
kilometer dan membentuk sumber air panas yang kini biasa dilalui oleh para
pendaki apabila mendaki dari jalur Cibodas.
 |
Tenda pedagang yang bisa kita temukan di
puncak gunung Gede.
|
 |
| Membuat
sarapan sebelum turun ke Cibodas. |
Padang rumput ini betul-betul luas,
memang terlalu mubazir rasanya apabila hanya didominasi oleh semak rumput,
Cantigi gunung ataupun tanaman Edelweiss saja. Namun tanaman yang sanggup
bertahan hidup diatas ketinggian 2.500 meter diatas permukaan laut seperti
disini ya hanya mereka. Andaikan saat itu bunga-bunga Edelweiss sedang
bermekaran, mungkin suasana di alun-alun Suryakancana akan jadi semakin
menarik, namun kita sadar betul kalau pesona dari bunga Edelweiss justru malah
mengundang bencana bagi tanaman itu sendiri. Meski memetik bunga Edelweiss
ataupun tanaman jenis lain sudah ada larangannya, namun masih tetap saja ada
orang-orang yang tidak memperdulikannya. Padahal bunga Edelweiss akan lebih
indah dipandang bila masih ada didalam satu kesatuan antara pohon, bunga juga
lansekap alam disekitar yang mendukung kecantikannya, dan bukan dalam keadaan
terpisah dari pohonnya. Sebagai tambahan, saya menyisipkan dialog antara Karen
dan Husin tentang Edelweiss Suryakancana dari sebuah novel Sarongge:
“Kita yang
menamakan diri pencinta alam, menjadi ancaman paling berbahaya dari kelestarian
alam. Kalaupun tidak menebangi cantigi, tidak membuat api unggun yang bisa
membakar padang edelweiss, tenda kita pastilah menutup kemungkinan bibit
edelweiss berkembang…… Makin banyak tenda dipasang, makin luas bibit edelweiss
yang tak sempat tumbuh… Kita para pencinta alam hanya bisa menikmati. Tetapi
apa yang kita lakukan untuk membayar kembali kepada alam, termasuk merawat edelweiss
di Suryakencana? Tak ada! Kita menutup mata, bahwa bunga abadi di alun-alun itu
sedang menuju kepunahan”
 |
Bukit hijau yang menyembul ini adalah bagian
dari puncak Gede, yang jadi salah satu landmark
di alun-alun Suryakancana.
|
 |
| Tanaman
Edelweiss dan Cantigi gunung yang daunnya berwarna cerah, terlihat harmonis di
cekungan lembah Suryakancana. |
 |
Sekelompok pendaki tampak baru saja tiba di
alun-alun Suryakancana pagi itu.
|
Langit berbalut biru cerah nan indah,
aku segera membangunkan Linda yang sedang tertidur didalam tenda untuk sarapan
sekaligus mengajaknya mengambil gambar selagi kabut dan awan mendung belum
datang. Selepas sarapan, saya, Linda juga Ipul memanfaatkan sisa waktu untuk
berfoto-foto, sementara Randi dan Riki memutuskan untuk tidur sebelum turun ke
Cibodas.
 |
Berlindung dari teriknya matahari dibawah flyingsheet tenda.
|
 |
Menikmati luasnya hamparan padang rumput di
lembah Suryakancana.
|
 |
| Foto
bersama sebelum membongkar tenda. |
8.
Puncak Gede (2.958 mdpl)
Pukul
12.45 WIB, kami berlima tiba di puncak Gede yang juga menjadi akhir dari
perjalanan kali ini. Saya dan Linda bersandar pada dahan pohon Cantigi yang
daunnya rindang melindungi kami dari terik matahari. Tidak jauh dari tempat
saya berteduh, ada sebuah tenda yang lebih menyerupai bivak dan digunakan
sebagai lapak untuk berdagang. Nasi uduk, rokok, mie instant sampai minuman
siap saji, semuanya tersedia di “café” tertinggi se-Jawa Barat ini. Para
pedagang tersebut rela membawa jerigen, termos, teko, wajan, kompor serta gas
tabung untuk keperluan memasak air atau membuat menu gorengan. Ditengah jalan
menuju puncak, saya memang beberapa kali berpapasan dengan pedagang di puncak
Gede yang baru saja mengambil air di alun-alun Suryakancana, perjuangan yang
cukup menguras tenaga. Tidak perlu disinggung pantas atau tidaknya mereka berdagang
di gunung, toh belakangan ini gunung
tidak hanya dieksploitasi oleh pedagang saja. Para pendaki yang bermental
oportunis pun sering menumbalkan keasrian alam khususnya gunung, demi sebuah
kepentingan. Kerapkali mereka mengatasnamakan kegiatannya dengan nama Lomba
Kebut Gunung, Lintas Alam, Operasi Bersih, atau yang hingga saat ini masih
digandrungi oleh para pendaki yaitu, Pendakian Massal alias Open Trip. Pada akhirnya, alam kembali
dijadikan kedok atau modus untuk mendulang keuntungan yang sebesar-besarnya.
Setelah acara selesai diadakan, maka disitulah awal penderitaan bagi para ranger dan warga setempat: gunungnya dibanjiri
lautan sampah logistik. Seperti yang pernah terjadi di Semeru pada tahun 2012,
dimana acara pendakian massal yang diadakan oleh salah satu produsen peralatan outdoor malah berubah menjadi bencana
bagi alam Semeru itu sendiri.
 |
Selfie bersama
Ari yang baru saja tiba di alun-alun Suryakancana bersama rombongan yang
berbeda.
|
 |
Berteduh dibawah pohon Cantigi.
|
 |
Alun-alun Suryakancana, puncak dan kawah Gede
dilihat dari Google map.
|
Tidak
jauh dari papan penunjuk arah, terdapat sebuah tugu triangulasi dengan tinggi
sekitar 1,5 meter yang sepertinya baru dibuat oleh pihak TNGGP. Hanya sangat
disayangkan, kebersihan tugu tersebut sudah “diperawani” oleh tangan usil oknum
pendaki yang mencoret-coret bagian ujungnya dengan menggunakan spidol hitam.
 |
Linda dan tugu triangulasi gunung Gede.
|
 |
Panorama kawah gunung Gede dan puncak
Pangrango yang diambil dari puncak Gede.
|
 |
Syaiful dan plang menuju alun-alun
Suryakancana.
|
Menjelang
pukul satu siang, intensitas awan dan kabut mulai meningkat sehingga puncak
Pangrango yang sejatinya menyembul kini jadi tidak terlihat. Pendaki lain mulai
berdatangan baik yang melalui jalur Putri ataupun dari Cibodas, suasana di
puncak Gede siang itu berangsur-angsur mulai ramai. Tidak ingin berlama-lama di
puncak, kami berlima pun segera meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalur
yang merupakan bibir kawah gunung Gede, angin mulai berhembus kencang dari arah
tenggara. Di sisi sebelah kanan jalur terdapat untaian sling yang memagari
bibir kawah, beberapa pagar beton juga tampak ada yang tercabut dari permukaan
tanah. Ya, gunung Gede memang gunung yang terbilang cukup baik pengelolaan
maupun manajemennya, bahkan almarhum Norman Edwin melalui sebuah tulisannya di
tahun 1984 pernah mengatakan;
“Gede-Pangrango
merupakan gunung yang terbaik pengelolaannya untuk suatu kegiatan pendakian,
ketimbang gunung-gunung lain di Indonesia. Disepanjang lintasan disediakan shelter-shelter bahkan pos. Malah
dibeberapa tempat dipasangi pagar untuk melindungi pendaki dari kemungkinan
terjatuh. Rambu-rambu tertentu juga dipasang di tempat-tempat yang strategis.
Tidak aneh, fasilitas tersebut disediakan lantaran kompleks gunung ini
merupakan suatu taman nasional”.
 |
Plang penunjuk arah yang terdapat di puncak
Gede.
|
 |
Suasana di puncak Gede beberapa saat sebelum
ramai dikunjungi para pendaki.
|
Taman
Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sendiri merupakan salah satu taman
nasional tertua di Indonesia dengan luas 22.851,03 hektare dan ditetapkan pada
tahun 1980. Kekayaan dan keindahan gunung Gede Pangrango tidak hanya menarik
hati wisatawan masa kini, seorang peneliti berkebangsaan Jerman di tahun 1819
yang juga pendiri dan direktur pertama Kebun Raya Bogor, Caspar Georg Carl Reinwardt
(1773-1854), tercatat sebagai orang yang pertama kali mendaki gunung Gede.
Pemberian nama pada beberapa pos yang ada di jalur pendakian pun sepertinya
masih memiliki relevansi dengan kondisi alam gunung Gede Pangrango di masa
lalu, sebagai contoh, Pos Kandang Badak. Dua tahun pasca Reinwardt mendaki
gunung Gede, datanglah sepucuk surat yang dialamatkan ke Buitenzorg pada awal
Agustus 1821.Kuhl dan Van Hasselt mengkalim kalau mereka baru saja melakukan
pendakian dan penelitian ke puncak Pangrango. Pada tahun itu, mereka sepertinya
kesulitan untuk menemukan jalur menuju puncak Pangrango hingga akhirnya mereka
menemukan dan mengikuti jejak serta lintasan Badak Jawa (Rhinocheros Sondaicus) yang ternyata malah mempermudah mereka
untuk menembus hutan menuju puncak Pangrango. Ketika itu, diperkirakan
disekitar air terjun Panca Weuleuh yang berada tidak jauh dari campsite Kandang Badak merupakan tempat
bermain bagi sekelompok hewan yang sekarang ini nyaris punah dari peredaran.
 |
| Tampilan
alun-alun Suryakancana yang terlihat dari puncak Gede. |
 |
| Siang
menjelang, mari kita pulang. |
 |
| Menyusuri
jalur berkerikil disepanjang bibir kawah. |
Hujan
mendera kami di jalur sebelum persimpangan Kandang Badak. Beberapa pendaki
kekinian yang tadinya tengah asyik berselfie
disisi jalan, sontak kocar-kacir manakala derasnya hujan membasahi seisi hutan.
Kami memutuskan untuk menepi di pos Kandang Badak sambil menunggu hujan mereda.
Tak lama kemudian hujan memang sempat reda, kami pun segera kembali menuntaskan
perjalanan hingga tiba di Cibodas selepas Isya. Alhamdulillah, kami berlima
telah menuntaskan perjalanan kali ini dengan selamat.
 |
Lubang kawah yang selalu mengepulkan asap.
|
 |
| Terpaksa
membuka flyingsheet untuk berlindung
dari derasnya hujan. |
 |
Suasana di pos Kandang Badak yang saat itu disesaki
dengan tenda-tenda pendaki.
|
Untuk
mendapatkan surat ijin memasuki wilayah konservasi atau simaksi dari pihak
TNGGP memang terbilang cukup rumit. Kita diwajibkan booking secara online dan
pembayaranpun diharuskan melalui transfer ke rekening milik TNGGP. Melampirkan
fotokopi KTP dan surat keterangan sehat dari dokter tetap menjadi prioritas
utama dalam memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh simaksi. Pengelolaan serta
manajemen semacam ini kerapkali ditiru oleh beberapa taman nasional lain di
Indonesia yang usianya terbilang masih muda. Pasca invasi pendaki ke Semeru
yang jumlahnya mencapai 2000 orang pada tahun 2012, pihak TNBTS akhirnya dengan
legowo mau meniru metode TNGGP untuk memberlakukan sistem booking online hingga saat ini.
 |
| Tampilan
ketika akan melakukan booking online
di situs resmi TNGGP. |
Selain
menerapkan peraturan yang rumit, beberapa taman nasional juga kadang membuat
kebijakan dengan menaikkan tarif simaksi. Tujuan ini dimaksudkan agar gunung
tidak terlalu mudah untuk dimasuki ataupun didaki oleh orang-orang yang
nantinya hanya berpotensi membawa masalah lingkungan, seperti memetik atau merusak
tanaman dan lain sebegainya. Namun sepertinya cara ini tidak begitu ampuh,
harga simaksi yang mahal akan tetap dibayar demi memenuhi ambisi mereka untuk
tetap bisa eksis di jejaring sosial. Manakala perusakan alam oleh beberapa
oknum pendaki sudah terjadi, maka masyarakat umum pun perlahan akan tersadar dan
memiliki opini tersendiri terhadap pendaki. Jangan salahkan publik seandainya
mereka beranggapan kalau pendaki hanya sebatas segel saja, tetapi secara mental
belum tentu bahkan tidak mencerminkan pribadi yang betul-betul cinta kepada alam
maupun lingkungan. Lantas kalau hanya untuk sekedar bereksistensi, untuk apa
lelah mendaki?
Jelajak
Langkah :
 |
| Randi
dan Ipul di terminal angkot Cipanas. |
 |
| Meniti
langkah menuju pos GPO gunung Putri. |
 |
| Beberapa
saat sebelum tiba di pos pemeriksaan. |
 |
Beristirahat di perbatasan antara ladang
warga dan pintu gerbang hutan.
|
 |
Papan ultimatum yang terpasang di jalur
pendakian, beberapa meter sebelum memasuki hutan.
|
 |
| Relax sejenak... |
 |
Saya dan Linda di pos I.
|
 |
| Linda
dibawah gapura pos I. |
 |
| Beberapa
pendaki yang masih berjuang untuk tiba di pos II. |
 |
| Kembali
beristirahat di shelter. |
 |
Ada cerita didalam kemasan sekotak susu.
|
 |
| Meluruskan
pinggang sesaat sebelum melanjutkan perjalanan. |
 |
| Mereguk
segelas teh tubruk hangat di pos III. |
 |
| Foto
terakhir sebelum meninggalkan pos III. |
 |
| Syaiful
dan dua gelas white coffee hangat. |
 |
| Menyelisik
yang enak untuk dibidik. |
 |
Menyambut senja di alun-alun Suryakancana bersama
hangatnya segelas kopi.
|
 |
| Linda
dan senja. |
 |
| Satu
angkatan, satu perjuangan. |
 |
| Selaras
dengan awan. |
 |
| Randi
sedang asyik menggoreng kentang. |
 |
| I’m
sorry, but it’s time for us... |
 |
Syaiful dan Randi sekembalinya dari sumber
air di alun-alun Suryakancana.
|
 |
Mulut
gua yang berada di lembah Suryakancana. Di waktu-waktu tertentu, gua ini biasa
digunakan untuk bertapa oleh para penganut Sunda Wiwitan.
|
 |
Sumber air yang terletak di cekungan lembah,
di tengah alun-alun.
|
 |
Gua yang berada tidak jauh dari gunung
Gumuruh.
|
 |
| Menikmati
kesunyian lembah, sebelum diinvasi oleh para pendaki yang akan menikmati akhir
pekannya di gunung Gede. |
 |
| Linda
dan kabut lembah. |
 |
| Entah
apa yang sedang ia pikirkan... |
 |
| Menikmati
panorama di alun-alun Suryakancana. |
 |
| Antara
memori dan pesona alam. |
 |
Bergaya didalam tenda. Mohon abaikan sosok
penampakan yang ada dibelakangnya.
|
 |
Dibawah lindungan flyingsheet merah.
|
 |
Menjelang siang hari, pendaki-pendaki pun
mulai berdatangan ke lembah ini.
|
 |
Foto di tugu triangulasi ketika baru saja
tiba di puncak Gede pada pagi harinya.
|
 |
| Randi
dan puncak Pangrango. |
 |
Linda dan
sekelompok pendaki yang pagi itu sama-sama melakukan summit.
|
 |
Pedagang ini tetap bertahan meski terik matahari
sudah menyengat sedemikian panasnya.
|
 |
Numpang bergaya di depan plang penunjuk arah.
|
 |
Apakah Pangrango mengenal slogan peace atau angka dua...?
|
 |
Kawah dan bibir jurang gunung Gede yang terbentuk dari
serangkaian letusan beberapa abad yang silam.
|
 |
| Randi
dengan landscape bukit-bukit di
sekitar Cianjur dan Bandung Barat. |
 |
| Dihadapan
bibir kawah. |
 |
Puncak Gede yang mulai didatangi beberapa
pendaki.
|
 |
| Saya
dan korban vandalisme. |
 |
| Karena
request dari seseorang, maka jadilah kami pendaki alay... |
 |
Pemandangan dari puncak gunung Gede yang
diambil saat tengah hari.
|
 |
| Sekitar
bibir kawah gunung Gede dan puncak Pangrango yang diambil dengan mode panoramic. |
 |
| Sekarang
waktunya untuk pulang. |
 |
| Berjalan
sambil menatap ke arah kawah... |
 |
| Cukup
melihat kawah dari jarak yang aman, jangan pernah menerobos tali sling
yang memang dipasang demi keamanan para pendaki. |
 |
| Sisi
bibir kawah yang dalam. |
 |
| Menanti
hujan reda di pos Kandang Badak. |